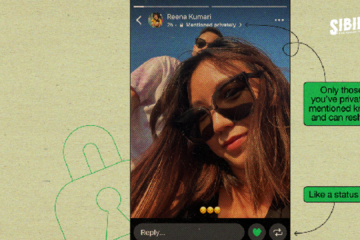Lagi Ramadan Katanya Setan Dibelenggu, Kok Hantu Masih?
Sebelum melangkah lebih jauh, penting untuk mengetahui perbedaan antara setan dan jin. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-An’am ayat 112, setan dapat menjadi sebutan bagi jin atau manusia. Jin yang bersifat durhaka adalah setan. Demikian juga umat manusia, apabila manusia bersifat durhaka maka dia memiliki sifat setan.
Jin sendiri adalah makhluk gaib yang berakal, memiliki kehendak, dan diberikan beban sebagaimana manusia. Sementara itu, setan adalah golongan jin yang bertugas menggoda dan mengajak manusia dalam kemaksiatan.
Dalam Islam, makhluk gaib seperti jin dan setan wajib diimani oleh umat Muslim. Sama halnya juga dengan malaikat dan iblis, makhluk-makhluk ini hidup beriringan dengan manusia di alam semesta.
Sementara di bulan Ramadan, menurut salah satu tafsir dari Ibu Baththal, setan benar-benar dibelenggu secara literal sehingga wujudnya tidak dapat berkelana mengganggu manusia.
Lantas, bagaimana dengan hantu?
Mudah saja, Islam tidak mengenal hantu—dengan konsep bahwa roh manusia yang meninggal lalu gentayangan. Hal ini dijelaskan dalam surat Al Mukminun ayat 99—100.
Kalau begitu pertanyaannya: mengapa masih ada kisah tentang hantu yang menghantui manusia? Dari sini, kita perlu mengulik lebih jauh konsep hantu itu sendiri. Apakah ia benar-benar entitas yang berdiri sendiri, atau hanya bagian dari narasi yang kita warisi dan yakini secara kolektif? Dengan kata lain, apakah hantu nyata, atau hanya ilusi yang dibentuk oleh budaya, psikologi, dan kepercayaan yang terus-menerus direproduksi dalam kehidupan sosial kita?
Jejaring Makna
Keyakinan pada hantu ternyata bukan sekadar mitos kuno, melainkan jejaring makna yang dibuat manusia—sebuah realitas intersubjektif yang lebih canggih dari aplikasi x. Hal ini senada dengan yang dijelaskan Harari (2015) dalam Homo Deus mengenai realitas uang dan negara. Sederhananya, kita ini mahir banget bikin cerita sampai kedengerannya nyata.
Nih, begini ceritanya: kita enggak mau ngaku kalau pocong atau wewe gombel cuma fiksi kelas remeh. Kenapa? Karena ternyata makhluk-makhluk imajiner ini punya fungsi sosial di masyarakat. Wewe gombel? Sosok seram yang dipakai orang tua untuk ngingetin anak-anaknya biar gak main terlalu malem. Pocong? Sosok yang sering dikaitin dengan pentingnya jalanin prosesi pemakaman secara benar. Dia ini kayak pengacara arwah yang protes gara-gara kafannya dilupakan—kuburan salah prosedur, ya sudah langsung demo (gentangayan)!
Semua ini bikin keberadaan hantu-hantu itu terasa nyata dan bermakna bagi kehidupan kita. Namun, sesungguhnya kepercayaan terhadap hantu-hantu ini cuma sebatas jejaring makna dengan cerita yang kita rajut bersama—seperti grup WhatsApp keluarga yang para orang tua percayai sebagai informan, padahal isinya cuma hoaks dan stiker doa selamat pagi.
Intinya, makna itu tercipta lewat semacam percakapan sosial yang terus-menerus saling menguatkan keyakinan dalam suatu lingkaran yang membesar dengan sendirinya. Setiap lingkaran konfirmasi timbal balik menguatkan jejaring makna lebih jauh sampai akhirnya kita cuma punya pilihan: percaya atau, yah, tetap percaya!
Panggung Teater Kesadaran
Bayangkan satu sekolah, katanya, lagi ada “kesurupan”. Yang dipanggil? Bukan dokter atau psikolog, melainkan dukun—sang superhero mistis dengan gaya sok introvert-nya.
Logikanya sederhana: siapa yang dipanggil, dialah sang juru tafsir realitas.
Dukun dipanggil? Dijamin interpretasinya akan seputar hal mistis, kesurupan. Namun, kalau yang dipanggil psikiater? Pasti mereka akan membedah kasus ini seperti detektif forensik kejiwaan, “Ini bukan hantu, ini skizofrenia atau histeria massal.” Gejala yang dianalisis pun berbeda: perilaku tidak terkendali, ledakan emosi ekstrem, dan persepsi terdistorsi—bukan aksi silat atau aing maung para makhluk gaib.
Masyarakat kita? Tentu lebih suka jawaban instan: “Itu hantu!” Persis seperti occam’s razor principle—memilih jawaban termudah sebagai yang benar dalam menjelaskan fenomena kompleks. Padahal, solusi semacam ini hanya menambah bias tanpa mengupas tuntas persoalan. Bahkan, fenomena seperti halusinasi visual bisa dijelaskan secara ilmiah.
- Sensitivitas sel batang di mata
Salah menangkap bayangan kecil sebagai gerakan yang diproses otak sebagai “hantu” yang sebenarnya tidak ada.
- Pareidolia
Otak manusia ini semacam mesin pencari pola yang tidak bisa diam. Makanya, kita bisa nemu “wajah” di objek acak, mungkin di batu, di awan, atau bahkan di roti bakar. Ini sebabnya hantu di setiap negara berbeda-beda karena budaya juga punya selera tersendiri soal sosok seram.
- Temporal Lobe Epilepsy
Gangguan neurologis ini bisa bikin halusinasi visual atau pendengaran—stimulasi pada lobus temporal bisa memicu sensasi kehadiran makhluk gaib.
Media Mistis si Kapitalis
Media, terutama televisi dan media sosial, berperan bagai dalang yang memperkuat kepercayaan masyarakat pada hantu.
Program televisi seperti reality show tentang dunia mistis atau dokumentasi pengusiran hantu kerap menyajikan narasi dramatis dengan segala setting-annya yang membuat masyarakat percaya pada kisah mistis sebagai fakta, bukan hiburan.
Media sosial pun tak mau kalah. Kisah “kesurupan massal” atau “penampakan hantu” bertebaran layaknya gosip ibu-ibu di tukang sayur, lalu disebarkan tanpa sehelai verifikasi. Bahkan, video atau foto yang tidak jelas asal-usulnya kerap dijadikan bukti keberadaan hantu. Algoritma media sosial berperan bagai juru kampanye mitos, yang dengan senang hati memprioritaskan konten sensasional. Sementara artikel ilmiah tengah berjuang mendaki tangga popularitas, video hantu melompat-lompat di puncak trending topic dengan ringannya.
Ironisnya, di balik layar, media ini beroperasi bagai dukun modern dengan YouTube channel-nya. Mereka menciptakan dan memelihara narasi hantu demi dua hal suci: AdSense dan subscribers. Lebih tepatnya, narasi hantu sebagai mantranya, AdSense sebagai rajanya, dan subscribers sebagai tumbalnya. Dampak sosial? Ibarat sampah yang dibuang ke sungai, tak terlalu dipikirkan. Atau, ibarat sampah yang tak dibuang, dibiarkan terus menumpuk—menjadi donatur watch time dan iklan di channel miliknya. Akibatnya? Masyarakat seperti masuk escape room mitos, tapi pintu keluar “akal sehat” dikunci, dan kuncinya malah dijual di Shopee dengan embel-embel limited edition.
Hantu itu Gak Ada
Banter-banter misalkan hantu itu “tetap tampak”, tentu saja, mereka bagaikan angka nol di ujian—tak ada nilainya. Begitulah yang diungkap oleh sejarah. Orang merajut jejaring makna, memercayainya sepenuh hati, tetapi cepat atau lambat jejaring itu pudar.
Seperti ilusi yang dikuatkan oleh sugesti, lingkungan, atau bahkan media, kekuatan mitos ini hanya bertahan selama ia terus disuguhkan sebagai “kenyataan”. Mirip seperti kepercayaan anak kecil pada peri gigi di bawah bantal tidur: semakin dipercaya, semakin nyata terasa, padahal cuma ilusi belaka.
Jadi, jawaban dari pertanyaan “mengapa di bulan Ramadan masih ada kisah tentang hantu yang menghantui manusia?” adalah karena manusia yang menginginkannya sendiri. Ketakutan kolektif yang terus dipelihara akan membuat hantu tetap tampak, meskipun tanpa dorongan supranatural—alias hanya imajinasi. Dengan kata lain, manusia sendirilah yang menciptakan, membentuk, dan mempertahankan eksistensi hantu, bahkan di bulan Ramadan ketika jelas-jelas setan telah dibelenggu.
Penulis: Raffael Nadhef Mutawwaf
Editor: Raismawati Alifah Sanda
Desainer: Muhammad Haeron