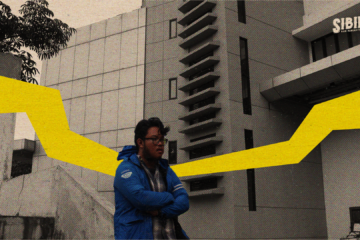Bahasa, kekuatan besar untuk menangkal serangan atau bahkan jajahan terhadap budaya lokal. Bahasa juga identitas yang menjadi ciri suatu negara, ciri kebudayaannya, dan ciri masyarakatnya. Apa yang sepatutnya dirasakan seseorang terhadap bahasa negaranya? Cukup sederhana, bangga.
Bangga bisa dianggap sederhana. Mungkin, bangga memang mudah untuk diucapkan. Namun apakah semudah itu menunjukkan rasa bangga itu? Apakah memahami bangga secara utuh semudah menyampaikan kata-kata, “Saya bangga”.
Kenyataannya, mungkin tidak. Menyampaikan bahwa seseorang bangga terhadap bahasa tidaklah semudah menuangkan rasa bangga itu dalam kehidupan sehari-hari. Buktinya jelas di negara ini. Bahasa Indonesia, bahasa yang telah resmi mempersatukan bangsa ini semenjak 28 Oktober 1928, secara perlahan dinomorduakan. Memang miris, mengingat puluhan tahun lalu ketika Hari Sumpah Pemuda, tertuang pada butir ketiga kata-kata, “Kami putra dan putri Indonesia menjujung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.”
Bahasa Indonesia dijadikan identitas yang begitu dibanggakan pada masa itu, identitas pemersatu. Kini, nampaknya rasa bangga itu semakin pudar.
Entah sengaja atau tidak, bahasa telah menjadi hal yang tidak terlalu diperhatikan pentingnya oleh tidak sedikit masyarakat Indonesia. Fenomena yang sangat mengecewakan terjadi saat ini, masyarakat Indonesia sendiri bahasa Indonesia sering kali menggeser dalam penggunaannya. Muncul sebuah gaya hidup di mana berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dianggap lebih modern. Mereka pun merasa lebih bangga ketika bisa menggunakannya di tengah masyarakat Indonesia. Namun, apakah penggunaan bahasa asing itu memang membuat mereka terlihat lebih… keren?
Ya atau tidak, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang menerima dirinya terjajah. Orang tersebut menerima identitas bangsanya digeser. Mereka pun ikut menggeser, karena mereka menerimanya.
Dalam Pasal 44 Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, tertulis “Pemerintah meningkatkan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.”
Menjadi bahasa internasional? Bila dalam UU terdapat tekad sekuat itu, pemerintah sebagai subjek yang diberi mandat untuk menjalankannya apa sudah berusaha merealisasikannya? Memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, setidaknya untuk skala sekitar Indonesia.
Kabar baiknya, Indonesia sudah agak berhasil untuk berjuang menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa kedua bagi penduduk Ho Chi Minh City, ibu kota Vietnam, dan di Australia bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer keempat. Ini semua masih proses, sebuah usaha kuat masih harus diperjuangkan, bukan hanya oleh pemerintah namun masyarakat luas. Masyarakat, yang menuangkannya dalam berbahasa sehari-hari, lalu karya-karya seperti film, lagu, karya satra, dan masih banyak lainnya.
Untuk ketiga karya yang saya sebutkan di atas, dapat dengan mudah kita melihat pergeseran penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, entah untuk keseluruhan isi, atau pun hanya judul karya.
Bila membahas salah satu karya sastra, yaitu novel, dapat dengan mudah kita menemukan begitu banyak novel karya anak bangsa yang tidak menghadirkan bahasa Indonesia secara seutuhnya. Ada begitu banyak novel yang dari judulnya saja sudah berbahasa Inggris, menunjukkan identitas bangsa orang lain, bukan bangsanya. Padahal, karya siapa novel tersebut? Anak Indonesia, bangsa Indonesia.
Apa mereka salah?
Tak ada jawaban pasti, tidak ada peraturan hukum yang mengatur hal tersebut memang. Namun, mengapa banyak novel Indonesia yang pada bagian judul menggunakan bahasa asing, padahal isinya berbahasa Indonesia?
Sri Izzati Soekarsono, penulis novel yang berhasil meraih rekor MURI sebagai penulis novel termuda karena karya pertamanya, Powerful Girls, menyatakan bahwa judul dalam bahasa Inggris selain lebih singkat, juga terdengar lebih menarik.
“Di era globalisasi ini, kalau menurut Izzati, penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris yang semakin meningkat itu sebenarnya tidak terelakkan, seperti memang sudah ‘masa’nya di mana orang-orang harus bisa berbahasa Inggris, salah satunya untuk survive,” ujar Izzati saat membahas tentang penggunaan bahasa asing di Indonesia saat ini.
Di sisi lain, perempuan muda yang telah menghasilkan enam belas novel (delapan di antaranya menggunakan bahasa asing pada bagian judul) tersebut menganggap, “Semua itu harus diimbangi, identitas sebagai warga negara Indonesia yang berbahasa Indonesia itu tidak boleh hilang, harus selalu diasah, di-update, diperbaharui.
Djarlis Gunawan, seorang Ahli Bahasa yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, menganggap negatif perilaku menggunakan bahasa asing pada bagian judul novel.
“Judul itu jendela untuk orang mengetahui isi novel tersebut, sekarang kalau judulnya saja sudah disekat dengan bahasa asing, bagaimana?” ujar Djarlis.
Dia pun menambahkan, “Sebuah bangsa bisa hancur dengan intervensi melalui bahasa.”
Memang tragis bila dibayangkan, namun sayangnya konsep yang dapat menghancurkan bangsa itu masih terjadi. Namun lebih lanjutnya, Djarlis juga menganggap bila dalam sastra memang ada kebebasan untuk penggunaan bahasa, jadi hal-hal tersebut memang sebenarnya diperbolehkan. Untuk sastra pun tak diperbolehkan ada peraturan hukum untuk mengatur bahasa yang digunakan sastrawan, karena memang mereka diberi kebebasan.
Bila membahas siapa yang salah atas fenomena ini, Djarlis menyampaikan dirinya sendiri sebenarnya malu karena penyebab utamanya adalah para ilmuwan bahasa yang tidak serius. Dia mencontohkan pada saat dirinya menulis di majalah Tempo tahun 1982, saat momen bulan bahasa, tulisannya yang mengkritik bahwa bahasa Indonesia semakin tergeser hanya didiamkan. Tak ada respon terhadap tulisannya.
Memang tragis fenomena penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, oleh novelis pada bagian judul bukunya. Namun, kesadaran harus segera dikembalikan kepada para anak bangsa ini.
Di satu sisi memang tak ada peraturan yang mengikat mereka untuk menghasilkan sastra berbahasa Indonesia atau tidak menyampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Namun, di sisi lain, mereka harus sadar bahwa penyampuran itu sejatinya tak memberikan efek lebih baik untuk karya mereka. Eksistensi bukan didapatkan dari hal-hal seperti itu, eksistensi bisa lebih terbukti dari bagaimana isi dan makna karya mereka.
Bila melihat ke belakang, dapat kita temukan karya-karya sastra lama yang luar biasa dari anak bangsa di mana penulisannya teratus persen menggunakan bahasa Indonesia. Sebuah karya sastra bisa terlihat lebih keren bukanlah karena bahasa asing yang penulis gunakan, banyak penulis telah membuktikannya.
“Agus Salim, Hamka, menguasai lebih dari sepuluh bahasa asing. Namun, mereka menyerap banyak bacaan asing, lalu di-filter, dan dilahirkan lagi dengan produk Indonesia, tidak mendompleng dari bacaan asing, kan tetap keren,” ujar DJarlis tentang kelebihan penulis lama.
Bila dibandingkan, Djarlis menambahkan lagi kalau banyak penulis sekarang yang ceroboh di mana seharusnya mereka menjaga bahasa mereka, bahasa Indonesia, dan tidak mengacak-acaknya.
“Bahasa Indonesia itu tidak kalah keren,” tambah Djarlis.
Untuk para novelis, Djarlis menyampaikan, “Kalian itu mau jadi pejuang dari sisi mana? Sekarang peperangan sudah tidak ada. Cobalah menjadi pejuang untuk mengamankan bahasa Indonesia-nya. Sadar bahwa kalian adalah bangsa Indonesia.”