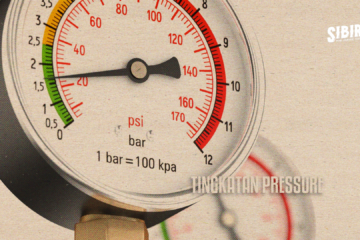Setiap kali rakyat marah, negara ataupun aparat selalu lebih lihai membuat dongeng ketimbang menjawab tuntutan. Kini muncullah “anarko”—makhluk imajiner yang dituding jadi biang kerok demonstrasi akhir Agustus sampai awal September. Selain makhluk imajiner, istilahnya pun imajiner: orang yang menganut anarkisme itu anarkis, bukan anarko. Tapi persetanlah, yang penting ada kambing hitam, mungkin begitu kata mereka. Sama seperti ’98 ketika etnis Tionghoa dijadikan sasaran, kini giliran rakyat dipaksa percaya bahwa semua kerusuhan tak lain ulah si hantu bernama anarko.
Padahal, anarkisme bukan tentang ideologi perusakan, melainkan penolakan terhadap otoritas hierarkis—ya, memang termasuk negara. Namun, makna anarkis malah mengalami peyorasi, terdistorsi oleh penguasa dan media massa, menjadi “perusakan”, “kekerasan”, dan “kekacauan”—termasuk entri di KBBI. Selaras dengan teorinya Alexander Wendt (dalam Zauzah, N. Z., 2024) mengenai “Anarchy is What States Make of It”, anarkis tidak pernah netral, tetapi konstruksi sosial: makna anarkis dibentuk oleh aktor-aktor politik sesuai kepentingan mereka. Jika negara ingin menjadikannya momok, maka anarkis akan dikonstruksikan sebagai perusak.
Sedikit berbeda dengan “perusak”, memang dalam pemikiran awal anarkis menyebut bahwa revolusi sosial perlu “kekerasan”. Namun, jangan salah kaprah; mesti kembali ke substansinya: revolusi sosial. Artinya, sebagaimana kata Errico Malatesta (dalam buku Blok Pembangkang), “Kekerasan itu diperlukan untuk menumbangkan pemerintah, sebab mereka juga menggunakan kekerasan agar kita tunduk,” kekerasan tidak akan pernah dilakukan jika pemerintah tidak membuat “tiang gantung” untuk warganya ketika menolak titahnya; atau, bahkan lebih luas: jika tidak ada pemerintah atau tidak ada otoritas hierarkis, anarkis tak akan ada dan tak perlu melakukan revolusi sosial.
Memang, dalam praktiknya ada organisasi Utopian, kelompok anarkis ofensif, yang memilih menyerang simbol-simbol kapitalisme—seperti properti korporasi besar—karena dianggap bagian dari mesin eksploitasi buruh. Jadi, bukan berarti semua aksi anarkis steril, tok, hanya saja targetnya punya logika: melawan otoritas dan modal yang menindas, bukan asal bakar fasum.
Daripada terus-menerus menyalahkan hantu imajiner alias si anarko itu, dan dianggap sebagai dalang perusakan fasum, lihatlah fenomenanya lebih makro: akar kerusakan ini lebih dari soal halte dibakar, yakni soal bagaimana “negara dan modal” saling bermesraan. Bagi anarkis, pertanyaan mendasarnya bukan “apa harus bakar fasum?”, melainkan “apa dan siapa yang sejak awal merusak hidup rakyat?”. Logika itulah yang jadi dasar keyakinan anarkisme: “Negara membutuhkan kapitalisme untuk melanggengkan status quo, sementara kapitalisme membutuhkan negara untuk melanggengkan akumulasi modalnya.” Lantas, bagaimana relevansi konkretnya dengan Indonesia hari-hari ini? Lihat fakta ini: Aguan secara terang-terangan berbicara pada Tempo bahwa ia menjaga wajah presiden (Jokowi), di mana ratusan investor yang antre ke IKN merupakan pepesan kosong. Tak perlu dielaborasi, ini terlalu jelas. Tidak heran, karena rezimnya yang bertitel “keberlanjutan”, ketika presiden ke-8 itu berkata: Hidup Jokowi!”
Nah, bagi para anarkis, itulah bentuk otoritarianisme—yang meski negara tersebut mengakui dirinya sebagai negara demokrasi. “Kontrak sosial”—negara dan pemerintah ada karena kontrak tiap individu yang merasa bahwa hak tiap individu akan terlalu bebas dan perlu dibatasi—inilah yang ditentang oleh Mikhail Bakunin, karena orang-orang terdahulu membuat kontrak tanpa meminta pendapat pada orang-orang di masa kini.
Kembali ke persoalan membakar fasum, pergerakan yang hanya perlu dilakukan oleh perlakuan individual, berbeda dengan gerakan anarkis. Pierre-Joseph Proudhon mengatakan, gerakan anarkisme harus menggunakan gerakan massa, bukan individu, sebagai motor revolusi. Misalnya, karena kegiatan anarkis bermacam-macam termasuk memproduksi zine dengan propaganda wacana, dalam demonstrasi masif kepada DPR, akan semakin efektif ketika anarkis menggiring kemarahan rakyat agar tidak hanya puas pada kontroversi legislatif, tetapi juga pada eksekutif dan yudikatif—soal eksekutif bisa saja terus menggoreng pemakzulan Gibran dan pelanggaran HAM Prabowo, sementara soal yudikatif bisa saja menggoreng vonis hakim terhadap Tom Lembong yang awur-awuran. Bukan malah hanya membakar-bakar bangunan atau fasum yang justru memungkinkan adanya “darurat militer”—yang berpotensi menghambat gerak demonstrasi dan anarkisme itu sendiri.
Berkaca pada gerakan anarkis di Indonesia yang pernah ada, misalnya: Samin di Sumatera Barat melakukan anarkisme terhadap pemerintah kolonial, tanpa kekerasan, dengan salah satunya tidak membayar pajak, dan kemudian diikuti oleh para pengikutnya, saminisme. Lalu, ada Affinitas yang mengadakan Food Not Bombs (FNB) di bunderan UGM yang banyak orang lalu lalang untuk menyasar kelompok marginal: tukang becak, pedagang asongan, atau orang melintas. Bukan sekadar beramal makanan gratis, Affinitas sekaligus memampangkan pamflet isu mengenai anti-otoritarianisme, serta membuka ruang diskusi dengan partisipan.
Dengan demikian, anarkisme tidak sesampah di bayangan orang. Yang lucunya, yang benar-benar merusak (keuangan) negara malah duduk manis di Senayan, tidak pernah disebut “anarko”. Ya, daripada denial dengan membuat kambing hitam pada “anarko”, sebaiknya berbenahlah, mengakulah bahwa gerakan sosial yang ada itu murni dari rakyat atas kekacauan negara. Berhenti mencari-cari musuh bersama dan berhenti sok tahu tentang anarkis!
Penulis: Raffael Nadhef Mutawwaf
Editor: Raismawati Alifah Sanda
Desainer: Naraya Raissa Aqila