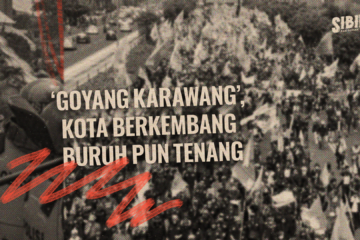Mengungkap realitas sudah menjadi tugas fundamental sebuah media. Ironisnya, perspektif yang masih dibatasi oleh tembok patriarki ini membuat isu-isu perempuan tidak dikuliti secara mendalam dan inklusif. Ruang redaksi yang seharusnya dapat membuka ruang gerak perempuan, justru mereproduksi budaya patriarki. Di sisi lain, kehadiran media alternatif menjadi “angin segar” yang dapat menjadi narasi tandingan yang lebih inklusif.
Dominasi Perspektif Patriarkis pada Narasumber dan Ilsutrasi Pemberitaan Kekerasan Seksual
Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan isu penting dan menjadi sorotan publik yang tak sepatutnya dianggap remeh. Isu ini kerap kali dianggap menarik oleh media massa karena berisi unsur-unsur yang dapat mengangkat penayangan berita (Bele & Fianto, 2025).
Bersamaan dengan ini, media massa juga memegang peran penting sebagai cerminan masyarakat dalam memandang perempuan. Ibarat pedang bermata dua, pemberitaan isu ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku, sekaligus menggiring opini publik tentang isu tersebut (Kiara, 2023).
Maka dari itu, cara media membingkai berita tentu memiliki dampak besar. Kabar baiknya, kini narasi yang menyudutkan korban sudah jarang terdengar. Melalui pengamatan kami pada media Detik.com (sebanyak 206 berita), kalimat-kalimat seksis nyaris tak terlihat lagi, diiringi dengan penekanan narasi kekerasan sebagai bentuk kejahatan.
Meskipun begitu, lebih dari setengahnya (52,3%) dari 350 pengutipan, Aparat Penegak Hukum mendominasi pemberitaan mengenai Kekerasan Seksual (KS). Disusul dengan politisi atau pejabat pemerintahan (19,1%) dan kategori Lainnya (18,0%) yang masih berhubungan dengan proses hukum (seperti saksi, pengacara, dsb).
Sedangkan pihak-pihak yang lebih dekat kepada korban, jumlahnya minim. NGO atau Organisasi independen seperti Komnas HAM atau Komnas Perempuan (5,4%), keluarga atau kerabat korban (4,3%), dan paling miris adalah aktivis/ahli yang hanya dikutip 3 kali (0.9%). Ini menunjukkan bahwa meskipun narasi berita tidak seksis, perspektif yang dipakai masih sangat patriarkis.
Menurut Humphries (2009), aparat penegak hukum dapat menjadi masalah karena pendapat mereka umumnya didasarkan pada sikap patriarki yang bias terhadap korban perempuan.
Selain dominasi sumber eksternal, penyertaan visualisasinya pun masih tergolong tak inklusif. Visualisasi ini kami kategorikan menjadi dua: ilustrasi dan foto asli. Dari 70 ilustrasi, lebih dari setengahnya (58,6%) bersifat tidak inklusif. Data ini memperkuat temuan sebelumnya, bahwa media cenderung menggunakan ilustrasi yang mendiskreditkan korban dan sangat patriarkis (Dzahabiyyah, 2024).
Masih banyak ilustrasi yang menampilkan perempuan sebagai seseorang yang lemah, tidak berdaya, bahkan jatuh pada objektifikasi. Hal ini menjadi PR besar yang perlu diperbaiki oleh media massa. Representasi yang tepat dan kuat penting untuk diperhatikan.
Secara keseluruhan, media Detik.com mulai meninggalkan kebiasaan narasi seksis. Namun, masih ada jalan panjang yang perlu diperbaiki. Media harus melepaskan dari ketergantungannya pada narasumber elite dan ilustrasi yang tidak inklusif. Tidak hanya informatif, tetapi juga berkeadilan dan berperspektif gender serta keberpihakan pada korban.
Dominasi Sumber Aparat dalam Pemberitaan Femisida
Kasus femisida atau pembunuhan berbasis gender terhadap perempuan, masih menjadi masalah sosial yang marak terjadi, baik secara global maupun nasional di Indonesia. Namun, media massa seringkali tidak memberitakan kasusnya secara adil (misal, Meyers, 1997; Pusparini, 2021).
Di sisi lain, penelitian terkait pemberitaan femisida di Indonesia pun masih belum banyak digarap (Ramadhani & Firdaus, 2025). Sehingga hal ini mendorong kami untuk melakukan analisis pemberitaan femisida di Indonesia.
Kami memonitoring pemberitaan terkait kasus femisida pada awal tahun 2025 (1 Jan-1 Mei). Kami mengambil data dari web Media Cloud dengan beberapa keyword yang relevan. Setelah proses pengumpulan data, clearing data, dan pengambilan sampel, kami menemukan 266 berita.
Tribunnews.com menjadi media yang paling banyak memberitakan kasus femisida (86.5%), disusul dengan jpnn.com (3.8%), republika.co.id (2.3%), detik.com (1.9%), dan lain-lain. Hal ini bisa dimengerti karena keterbatasan Media Cloud, tidak semua media online dapat ditemukan dalam web tersebut.
Salah satu kasus femisida yang mendapatkan perhatian media massa adalah kasus yang menimpa jurnalis asal Kalimantan Selatan, Juwita. Tak heran, data kami pun menunjukkan berita terkait kasus Juwita paling banyak ditemukan (179 berita atau 67.3%). Kasus kedua yang sempat ramai di media sosial juga adalah kasus femisida Feni Ere (14 berita atau 4.5%). Kasus lainnya hanya beberapa kali diberitakan oleh media massa.
Tanpa mengecilkan kasus Juwita, nyatanya para korban lainnya tidak diberikan ruang yang sama besarnya. Korban yang merupakan seorang jurnalis dan pelakunya anggota TNI, menjadi faktor yang memungkinkan kasus ini mendapat tekanan publik dan sorotan luas, termasuk di media massa. Sementara itu, beberapa korban lainnya terinvisibilisasi atau tidak mendapatkan proporsi ruang yang sama.
Selain masalah proporsionalitas jumlah berita, media massa pun acapkali menggunakan sumber eksternal, daripada sumber internal. Bahkan dalam kasus yang pelakunya seorang aparat pun, media lebih banyak memberikan ruang terhadap aparat. Dari keseluruhan narasumber (sebanyak 567), hampir setengahnya (267 atau 47.1%) merupakan aparat, seperti anggota kepolisian dan TNI.
Penegak hukum menjadi sumber kedua yang paling banyak dikutip. Padahal penegak hukum serta aparat justru berpotensi mendatangkan masalah, karena pendapat mereka umumnya didasarkan pada sikap patriarki yang bias terhadap korban perempuan (Humphries, 2009). Sumber internal, seperti kerabat, keluarga, dan ahli justru diberikan ruang yang lebih sedikit.
Padahal kerabat dekat dan ahli merupakan narasumber yang sangat mungkin paling paham terkait kondisi korban. Hal ini bukanlah kasus tunggal, sebab dalam banyak kasus lain, media massa pun memang memiliki ketergantungan pada sumber-sumber eksternal (Bullock dan Cubert, 2002; Taylor, 2009; Richards et al., 2011).
Lalu mayoritas kasus femisida terjadi dalam relasi intim (intimate femicide), terutama oleh pacar korban (79,7%). Hal ini menguatkan temuan sebelumnya, bahwa femisida seringkali terjadi di ranah privat dan hubungan romantis (Zárate-Cartas & Molina-Villegas, 2024).
Meskipun begitu, femisida tidak berarti menjadi masalah privat semata, sebab masalah ini berakar dari konstruksi sosial di masyarakat yang cenderung patriarkis dan diskriminatif (Hudson, et al. 2012; Erjem, 2024).
Namun, mirisnya, hampir 8 dari 10 berita (79,7%) hanya menyajikan femisida sebagai kasus individu, bukan sebagai masalah sosial. Hanya 54 artikel (20,3%) yang membahas femisida dalam kerangka yang lebih luas.
Di satu sisi, positifnya, 97% berita tidak menyalahkan korban. Meskipun begitu, masih terdapat 8 artikel (3%) yang cenderung menyalahkan korban secara tidak langsung. Misalnya, dengan narasi utama yang berfokus pada kondisi kejiwaan pelaku, menyatakan adanya masalah internal antara pelaku dan korban, dan berbagai narasi yang berfokus pada perilaku korban yang memicu kekerasan.
Meskipun jumlah yang kami temukan sedikit, hal ini tetap menjadi catatan penting bagi media untuk ke depannya memberitakan kasus femisida yang adil dan berpihak pada korban. Pun tidak menutup kemungkinan, banyak berita lain (di luar data analisis kami) masih menggunakan narasi yang menyalahkan korban, secara langsung ataupun tidak (Gillespie et al., 2013; Brodie, 2019; Busso et al., 2020; Akbaş & Ceylan-Batur, 2023;).
Secara umum, pemberitaan femisida di Indonesia masih belum ideal. Beberapa hal yang penting untuk diperbaiki ke depannya di antaranya, memberikan ruang lebih banyak kepada narasumber internal, memberikan ruang yang sama kepada seluruh korban, menggunakan narasi yang inklusif, dan tidak mengindividualisasikan masalah femisida yang merupakan isu struktural.
Kerentanan Kondisi Jurnalis Perempuan Saat Ini
Meski kini perempuan sudah menjadi bagian dalam dunia pers yang acapkali diidentifikasi sebagai profesi maskulin, dominasi laki-laki masih tidak dapat dipungkiri. Mengacu pada laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terdapat ketimpangan yang cukup besar antara jurnalis perempuan dan laki-laki di luar Jakarta.
Perbedaan yang cukup signifikan antara jurnalis perempuan dan laki-laki menjadi salah satu penyebab tindakan diskriminasi terhadap jurnalis perempuan masih berkibar di ruang redaksi. Seperti, hak cuti haid/menstruasi (68%) yang masih mendapat komentar negatif dari atasan serta rentan dirumahkan karena dianggap tidak produktif.
Kemudian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jurnalis perempuan rentan mengalami kekerasan seksual (82,6%), baik dari dalam lingkungan kerja maupun masyarakat luas. Salah satu yang kerap dialami adalah body shaming secara langsung (58,9%) maupun daring (48,6%). Ujaran tersebut tidak hanya diterima dari masyarakat luar, tetapi dalam ruang redaksi bahkan dapat dilontarkan oleh rekan jurnalis perempuan.
Selain itu, dalam praktiknya, jurnalis perempuan sering dipandang lebih lemah secara biologis dan psikologis, sehingga dianggap kurang layak untuk menjalankan tugas jurnalistik yang dianggap berat dan berisiko, seperti liputan lapangan malam hari atau peliputan isu-isu kontroversial (Aldi, 2023).
Pandangan ini tidak hanya membatasi peluang perempuan dalam karir jurnalistik, tetapi juga memperkuat stereotip gender yang merugikan secara sistemik.
Pada akhirnya, temuan analisis konten berita kami pun tidak mengherankan jika melihat kondisi ruang redaksi dan jurnalis perempuannya. Pemberitaan yang cenderung didominasi perspektif patriarkis tidak lahir dari ruang hampa, melainkan rutinitas dalam ruang redaksi itu sendiri yang masih diskriminatif terhadap perempuan.
Media Alternatif sebagai Narasi Tandingan yang Berspektif Gender
Secara umum media massa seringkali dibedakan menjadi dua jenis, yakni media mainstream dan media alternatif. Kedua jenis media ini memiliki ciri khasnya tersendiri yang berbeda.
Media mainstream atau media arus utama umumnya merupakan jenis media yang berorientasi pada kepentingan komersial melalui jangkauan khalayak yang luas, pendapatan iklan, langganan, dan sponsor. Oleh karena itu, konten yang disajikan oleh media mainstream sering kali disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingannya. Beberapa media mainstream di Indonesia, misalnya Detik, Kompas, CNN Indonesia, dan sebagainya.
Sebaliknya, media alternatif dibuat oleh individu atau organisasi kecil yang tidak memiliki sumber daya finansial atau dukungan kelembagaan seperti media mainstream. Media alternatif berorientasi pada kepentingan non-komersial dan bertujuan untuk menyuarakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti kaum minoritas, alias voice of the voiceless.
Menurut Birowo (2004), media alternatif merupakan media yang berorientasi pada masyarakat dan ikut bermain dalam membangun wacana di public sphere, sehingga media ini diharapkan dapat melayani kelompok yang termarjinalisasi.
Indonesia memiliki cukup banyak media alternatif online dengan fokus dan tujuan yang berbeda-beda, salah satunya adalah Konde.co yang merepresentasikan isu gender dan perempuan. Konde.co merupakan media yang mengusung perspektif perempuan dan minoritas yang hadir secara bilingual (bahasa Indonesia dan Inggris).
Melalui forum diskusi dan kolaborasi liputan, Konde.co juga mendorong terbentuknya jejaring media perempuan dari berbagai daerah. Platform Women News Network (WNN) muncul sebagai hasil dari kerja sama ini dan membantu memperkuat peran perempuan dalam media lokal.
Selain Konde.co, media alternatif lainnya yang berdiri khusus untuk membahas isu gender adalah Magdalene.co. Magdalene.co merupakan media feminis interseksional yang telah berdiri sejak 2013 dan terkenal dengan pendekatan jurnaismenya yang solutif, kritis, dan inklusif. Kekerasan berbasis gender, hak-hak LGBTQ+, stigma tubuh, spiritualitas inklusif, dan partisipasi politik perempuan adalah topik yang sering diangkat oleh media ini.
Magdalene.co tidak hanya menyediakan konten dalam berbagai format seperti podcast, video, dan esai, tetapi juga bekerja sama dengan program Investing in Women untuk mengajar jurnalisme yang sensitif akan isu gender.
Selain Konde.co dan Magdalene.co, masih terdapat juga berbagai media alternatif lainnya yang seringkali vokal dalam mengarusutamakan perspektif gender dalam pemberitaannya.
Misalnya, Project Multatuli (PM) yang mengusung visi voice the voiceless, termasuk mengangkat suara yang dipinggirkan, komunitas yang diabaikan, dan isu dasar yang disisihkan. PM pun turut mengawal berbagai isu terkait perempuan dan pemberitaan yang berspektif gender.
Selain itu, dalam skala lokal, BandungBergerak.id menjadi salah satu media alternatif yang vokal dalam menyuarakan isu perempuan. Media yang berbasis di Bandung ini turut mengawal berbagai isu mengenai perempuan dan gender. Hal ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan yang diterbitkan, agenda diskusi yang digelar, maupun menyediakan ruang-ruang bagi suara perempuan untuk hadir dan dapat dibaca oleh publik.
Pada akhirnya, media alternatif ini pun salah satunya hadir dari kekecewaan terhadap media mainstream yang seringkali mengabaikan suara-suara terpinggirkan, termasuk perempuan. Media alternatif hadir dengan memberikan narasi alternatif yang lebih inklusif dan berkeadilan. Mereka hadir untuk menantang narasi dan dominasi patriarki yang menghinggapi ekosistem media serta masyarakat secara luas.
Pentingnya Kehadiran Media yang Lebih Berkeadilan
Kajian ini mencoba untuk menghadirkan diskusi terkait realitas perempuan di media. Melalui analisis konten dan pembacaan atas realitas media saat ini, nyatanya media masih sangat didominasi oleh perspektif yang patriarkis dan diskriminatif.
Ke depan, media mainstream perlu membenahi kondisi ini dengan menghadirkan pemberitaan yang lebih inklusif dan berkeadilan terhadap perempuan. Selain itu, ruang redaksi seharusnya dapat menjadi ruang yang inklusif dan tidak membatasi perempuan.
Kehadiran media alternatif menjadi sinyal positif yang perlu diperhatikan media lainnya secara umum. Keberpihakan pada perempuan bukanlah suatu hal yang haram, melainkan keharusan. Media seharusnya dapat berdiri pada kepentingan publik, terutama bagi mereka yang seringkali terpinggirkan, termasuk perempuan.
Penulis: (Sibiru) Alya Fitri Ramadhani, Maulida Hasna H., N. D. Carla Sitorus, dan Raismawati A. Sanda;(Kompilasi) Akhmad Aziz Nanda Saira dan Yoga Firman Firdaus
Editor: Akhmad Aziz Nanda Saira, Yoga Firman Firdaus, dan Maulida Hasna H.
Desainer: Baiqa Jasmine Effendie